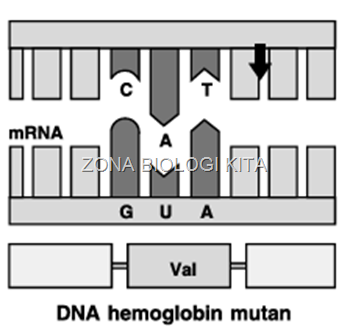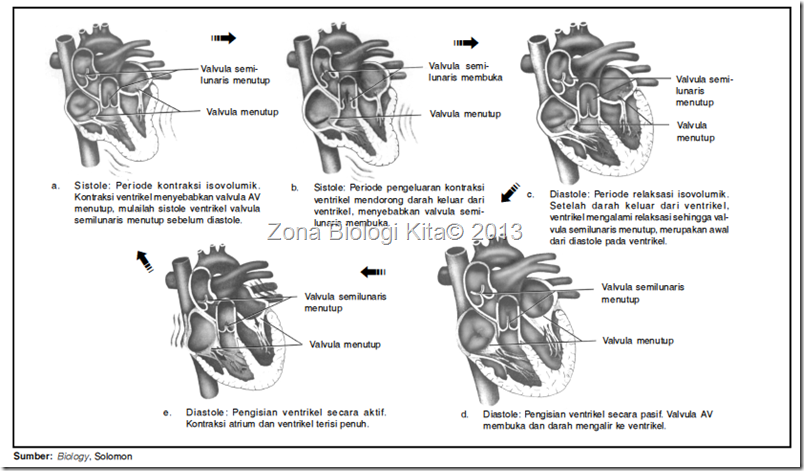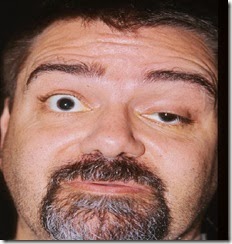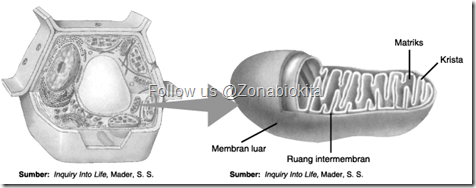Manusia dengan jumlah kromosom diploid (2n) 46 buah kromosom (44A + XX atau 44A + XY) jika mengalami mutasi menghasilkan aneuploid trisomi, kromosom individu tersebut akan bertambah satu menjadi 47 kromosom (2n +1). Pada manusia, mutasi karena aneuploid ini dapat mengakibatkan kelainan atau penyakit. Meskipun hal ini membahayakan individu penderita, kelainan tersebut jarang dapat diturunkan, karena umumnya penderita menjadi mandul dan tidak dapat menghasilkan keturunan. Contoh penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh mutasi kromosom aneuploid yaitu sindrom Down, sindrom Klinefelter, dan sindrom Turner. Berikut dipaparkan beberapa kelainan akibat mutasi kromosom.
1) Sindrom Turner
Gambar: Kromosom pada orang dengan Sindrom Turner
Sindrom Turner ditemukan oleh H.H. Turner tahun 1939. Ciri-ciri sindrom Tuner sebagai berikut.
Sumber: Wikipedia
a) Kariotipe: 45 XO (44 autosom + satu kromosom X) diderita oleh wanita.
b) Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi sperma yang mengandung kromosom X.
c) Tinggi badan cenderung pendek.
d) Perkembangan alat kelamin terlambat (infantil).
e) Sisi leher tumbuh tambahan daging.
f) Bentuk kaki X.
g) Kedua puting susu berjarak melebar.
h) Keterbelakangan mental.
Berikut adalah video tentang mereka yang memberi kesaksian dan berbagi kisah tentang SIndrom Turner:
2) Sindrom Klinefelter
Gambar Kromosom pada orang yang hidup dengan Sindrom Klienefelter
Sumber: Wikipedia
2. Sindrom Klinefelter ditemukan oleh Klinefelter tahun 1942. Ciri-ciri sindrom Klinefelter sebagai berikut.
a) Kariotipe: 47, XXY (kelebihan kromosom seks X) diderita oleh pria.
b) Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY, atau sel telur yang membawa kromosom XX dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom Y.
c) Bulu badan tidak tumbuh.
d) Testis mengecil, mandul (steril).
e) Buah dada membesar.
f) Tinggi badan berlebih.
g) Jika jumlah kromosom X lebih dari dua mengalami keterbelakangan mental.
Gambar orang yang hidup dengan Sindrom Klinefelter (Sumber : Wikipedia)
3) Sindrom Jacob
Sumber gambar: Earthlink
Sindrom Jacob ditemukan oleh P.A. Jacobs tahun 1965. Ciri-ciri sindrom Jacob sebagai berikut.
a) Kariotipe: 47, XYY (kelebihan kromosom seks Y) diderita oleh pria.
b) Sindrom ini terjadi karena sel telur (X) dibuahi oleh sperma YY (akibat gagal berpisah).
c) Berperawakan tinggi.
d) Bersifat antisosial dan agresif.
e) Suka melawan hukum.
4) Sindrom Down
Gambar: Sketsa wajah anak dengan Down Syndrom
Gambar: Kromosom sindrom Down (Sumber: Wikipedia)
Sindrom Down ditemukan oleh J.L. Down tahun 1866. Ciri-ciri sindrom Down sebagai berikut.
a) Kariotipe: 47 XX atau 47 XY.
b) Mongolisme, bertelapak tebal seperti telapak kera.
c) Mata sipit miring ke samping.
d) Bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, serta gigi kecil-kecil dan jarang.
e) IQ rendah (+ 40).
Namun, bukan berarti anak dengan Down Sindrom hanya menjadi beban bagi orang lain. Mereka pun juga bisa berprestasi dan berkiprah bagi sesamanya. Berikut video inspirasional tentang anak-anak yang hidup dengan Sindrom Down:
Berikut juga video dari ISDI Indonesia tentang anak-anak Down Syndrome yang memiliki bakat di bidang seni musik.
5) Sindrom Edwards (Trisomi 18)
Gambar: Anak dengan Syndrome Edwards (Sumber: health)
a) Kariotipe: 45 A + 18 + XX atau 45 A + 18 + XY.
b) Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur.
c) Tulang tengkorak lonjong.
d) Dada pendek dan lebar.
e) Kedudukan telinga rendah dan tidak wajar.
f) Mulut kecil.
9) Mengalami keterbelakangan mental.
6) Sindrom Metafemale
a) Kariotipe: 44 A + XXX diderita oleh wanita.
b) Sindrom ini terjadi karena sel telur yang mengandung kromosom XX (akibat gagal berpisah) dibuahi oleh sperma X.
c) Payudara tidak berkembang.
d) Menstruasi tidak teratur, dan steril.
e) Mengalami gangguan mental.
f) Pada umumnya tidak berusia panjang.